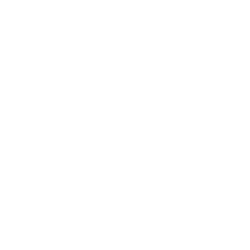Fitria Rachmawati Zain
(Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia (TBI), IAIN Surakarta)
#BanggaIAINSurakarta
Seminar maupun lokakarya sangat digemari oleh mahasiswa layaknya orang yang haus akan ilmu. Mahasiswa yang mengikuti seminar maupun lokakarya tentu tak akan lupa untuk berfoto. Mahasiswa mengaku cukup paham saja dengan apa yang disampaikan di suatu acara dan selebihnya lebih banyak diisi dengan berfoto riang. Dimanapun, mahasiswa manapun suka untuk ber-swafoto atau selfi.
Begitu pula hal yang terjadi saat kuliah perdana IAIN Surakarta beberapa saat yang lalu. Kuliah perdana yang seharusnya membuat mahasiswa lebih mengerti tentang Islam, tetapi terkesan hanya formalitas. Beberapa mahasiswa mendengarkan sekadarnya, tanpa ada niat untuk mencatat ataupun mendengarkan dengan seksama. Salah satu kebanggaan mengikuti seminar atau lokakarya terletak pada foto dengan kawan-kawannya atau bersama pembicara. Sebelum kuliah perdana dimulai, mahasiswa sudah siap dengan gawai canggihnya, berfoto dengan latar belakang pamflet. Pada akhir sesi mahasiswa rela berbaris untuk berfoto dengan pembicara.
Saya yakin foto-foto itu tak akan berhenti di handphone ataupun laptop, mahasiswa dengan pede memasang foto diberbagai media sosial. Foto hanya dianggap “barang manipulatif” dan penuh rekayasa, sekaligus ajang eksistensi diri berujung pada pamer di berbagai media sosial. Dengan adanya instagram, lebih mudah memajang foto. Foto sudah menjadi gaya hidup.
Mahasiswa yang identik dengan hal akademik mulai terkikis. Pengalaman pendidikan yang sesungguhnya berlalu begitu saja, dan yang ada hanya pengalaman-pengalaman palsu. Mahasiswa yang berfoto dengan senyum lebar, berbaris rapi bersama Azhar Ibrahim, Ph.D kala itu juga sebagai pemalsuan semata.
Nyatanya memang sangat mudah memanipulasi diri sendiri, juga dengan gampangnya mahasiswa termanipulasi dengan hal itu. Bre Redana dalam essay-nya Histeria Selfi (Kompas, Minggu 12 Juni 2016), semua image tak lagi menjadi sesuatu hal penting, praktik memotret mengambil alih, menjadi lebih penting daripada foto itu sendiri. Keagungan berfoto melulu menjadi fokus utama dalam berbagai acara.
Hal yang terpenting dalam suatu acara bukan lagi isi dari acara tersebut, bukan lagi rasa keinginan tahuan untuk mendengarkan seksama yang diutarakan pembicara melainkan lebih disibukkan dengan berpakaian sedemikian apik dan gawai yang siap memotret. Mahasiswa tak lagi disibukkan dengan menyiapkan materi yang disampaikan. Sebelum dimulai bukan buku catatat yang bertindak, tapi gawai canggih yang siap menampilkan wajah sumringah dengan latar belakang backdrop acara.
Tubuh sungguh punya hak untuk bercerita mengenai kenangan, kejadian, bahkan sejarah dari foto. Tentu ini berbeda dengan foto Moh. Yamin saat ber-pose dengan anggota Kongres Pemuda II, terpampang di Sepenggal Sumpah dari Rumah Kos (Tempo, 18-24 Agustus 2014). Moh. Yamin mengatakan berfoto bukan untuk eksistensi terhadap diri untuk penghargaan, namun sebagai bukti sejarah. Tentu Moh. Yamin dapat menceritakan kepada kita perihal fotonya sebagai anggota Kongres Pemuda II. Moh. Yamin dapat mempertanggungjawabkan, apa yang ada di foto. Bukan hanya semata-mata untuk pembuktian ke publik. Perihal ini belum tentu sama dengan mahasiswa yang mengikuti kuliah perdana. Melalui foto diri dapat berbicara banyak hal, busana, waktu, dan peristiwa.
Euforia berfoto akan terus-menerus berlanjut dalam satu acara. Mahasiswa akan mengikuti berbagai seminar atau acara yang ngtren hanya untuk berfoto. Keriuhan foto-foto merupakan etalase yang palsu, sungguh mengganggu. Maulana Kurnia Putra dalam Foto dan Sejarah yang Bergerak (2015:38), foto tanpa makna dan kenangan hanya akan jadi narsisme semata, berakibat menjatuhkan kebermaknaan diri dalam ruang sosial. Foto-foto itu akan selalu dibayang-banyangi banjir pujian dan komentar.
Tak malukah hanya tersenyum lebar dan berpose dengan embel-embel mengikuti acara seminar atau sejenisnya. Apakah pantas perbuatan itu dilakukan oleh seorang akademisi??? Sudahi sajalah. Mari berbenah diri.