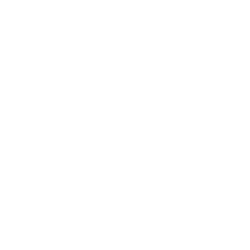Oleh: Lutfi Aminuddin
(Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia Semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)
Penulis Novel Negeri Bahagia Skandinavia (2017)
Budaya tidak bersifat matematis, atau sesuatu yang eksak. Budaya merupakan sebuah fenomena yang lentur, dialogis, cair, dan bisa berubah pemaknaanya di dalam masyarakat. Oleh karenanya, budaya mampu berasimilasi, dengan budaya-budaya lainya, lalu membentuk sebuah kebudayaan baru.
Sifat budaya yang seperti itulah, maka hari ini kita tidak dibuat heran. Ada orang-orang yang memakai celana kolor, kaos oblong, dan celana pensil, lengkap dengan sepatu pantofel yang ”necis”, merupakan suatu fenomena yang biasa. Kalau kita mundur ke-3 abad yang lalu, pasti kita dibuat heran, saat melihat ada orang Jawa yang tidak mengenakan blankon.
Di zaman sekarang, tren yang terjadi sebaliknya. Banyak orang yang kini memakai celana dan kaos oblong. Keganjilan justru terjadi, saat didapati ada orang-orang yang sedang berada di keramaian, ada orang bertelanjang dada tanpa pakaian. Taruhlah lagi saat kita melihat gadis manis sedang memakai sanggul, dan berkebaya Jawa lengkap. Pasti kita akan mengira, wanita itu akan jadi manten, atau sedang mengikuti kegiatan pawai budaya Hari Kartini.
Proses pergumulan budaya, dan pergumulan sejarah yang lama, membuat budaya mengalami perubahan kesan. Saat sebuah budaya bersentuhan dengan budaya-budaya lain, maka akan terjadi tukar-menukar antar budaya, tukar-menukar antar tradisi, atau bahkan terjadi penghilangan budaya itu sendiri, oleh kesuperioritasan budaya lain.
Dengan memahami cara kerja pembentukan budaya yang semacam itu. Mestinya ada kesadaran dalam diri kita, bahwa proses terciptanya budaya tidak seratus persen original, tetapi ada proses pinjam – meminjam (take and give) di dalamnya. Kecuali jika kebudayaan itu tercipta di dalam masyarakat terisolasi, dalam hal ini seperti pada masyarakat Eskimo, dan Inuit. Produk kebudayaan yang tercipta di masyarakat Eskimo dan Inuit cenderung lebih ekslusif, jika dibandingkan dengan produk-produk kebudayaan lainya yang non-terisolasi.
Cara kerja-kerja budaya yang semacam itu, sama saja dengan cara kerja sebuah bahasa. Bahasa sebagai produk dari kebudayaan manusia, juga tidak terlepas dari perubahan-perubahan pemaknaan yang berkembang di dalam masyarakat. Suatu bahasa bisa berkembang, atau bahkan hilang, tertelan oleh kesuperioritasan bahasa lain.
Ambil saja contohnya, dulu orang-orang Jawa, kerap sekali mengucapkan “uwos” untuk penyebutan yang similar dengan beras. Belakangan, pemakaian kata uwos dalam masyarakat tutur Jawa, sudah tidak banyak digunakan lagi. Pemakaian kata beras lebih sering digunakan, seiring dengan perkembangan bahasa yang bersifat mana suka (arbitrer).
Di dunia bahasa sendiri, pemakaian suatu tuturan di dalam masyarakat, erat kaitannya dengan pinjam meminjam kebudayaan itu sendiri. Misalnya saja kata terjemah, yang diserap dari bahasa Arab “tarjamah”. Setau saya, kegiatan terjemah-menerjemahkan secara budaya memang identik sekali dengan kebudayaan Arab. Apalagi dalam sejarah Islam Klasik, kita tahu betul bahwa perpustakaan Baitul Hikmah, menjadi corong beradaban ilmu, di mana di perpustakaan itu terjadi kegiatan penerjemahan besar-besaran.
Ketika itu teks-teks Yunani, diterjemahkan begitu masif oleh sarjana-sarjana Islam, di bawah kekuasaan Dinasti Abasiyah. Di masyarakat Nusantara sendiri ketika itu, tidak banyak aktivitas penerjemahan yang sebegitu masif seperti di dunia Arab. Untuk memahami sebuah teks, orang Nusantara lebih sering belajar langsung kepada guru-guru yang mumpuni, yang memang memahami betul, bahasa yang ada pada teks tersebut.
Maka memang sudah seharusnya KKBI menyerap kata terjemah secara harfiah, untuk menjelaskan kegiatan pengalih bahasaan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, yang memang khaisais dengan budaya Arab. Mengutip pendapat Catford (1974:26), “penerjemahan tipe harafiah biasanya diaplikasikan jika struktur kalimat bahasa target yang diterjemahkan berbeda dengan struktur kalimat bahasa sasaran”. Apa yang dikatakan Catford memang ada benarnya. Tapi kendati begitu lema “alih bahasa”, sebagai pengganti dari terjemah sendiri sudah masuk ke dalam kamus. Walaupun kita akui betul, jika kata terjemah lebih sering digunakan dalam masyarakat tutur kita.
Demikian juga dengan bahasa-bahasa lain. Saya bersyukur ketika KKBI juga menyerap lema “twit” yang bersimilar dengan cuitan.
Pemakai bahasa kini lebih banyak memiliki variasi bahasa, bisa memilih cuitan atau twit. Hanya saja, masyarakat perlu bijak, menggunakan variasi bahasa-bahasa yang sudah terdapat di lema kamus. Tentu penggunaanya harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam sosiolingustik.
Misalnya saja saat kita sedang berada di forum ilmiah, masyarakat tutur Batak. Kendati kata ”bujang” itu masuk dalam lema kamus yang artinya seorang manusia yang belum menikah. Sebisa mungkin kiita hindari penggunaan kosa kata itu saat lawan tuturnya masyarakat Batak. Bujang dalam pemaknaan masyarakat Batak bermakna ganda, jika konteks kata yang mengikutinya tidak tepat, bujang bisa diartikan sebagai “brengsek”. Oleh karenanya, penutur lebih aman menggunakan diksi lajang saja, jika berada dilingkungan tuturan Batak.
Oleh karena itu, memahami cara kerja bahasa amat begitu penting. Penutur harus tahu bahwa sifat bahasa bisa berubah pemaknaanya di satu wilayah lain, yang berbeda dengan wilayah lainnya. Pengetahuan tentang logika-logika berbahasalah, yang akan membuat sebuah tuturan dapat berterima di dalam masyarakat.
Daftar Pustaka
Catford, M. 1974. A Linguistik Theory of Translation. London: Oxford.